Sejauh usia saya terbentang hingga beberapa hari lalu, ada satu pemahaman yang mungkin dari dulu belum berubah sama sekali di benak saya. Bahwasanya kita, manusia berjuang keras setiap hari, belajar giat, bekerja tekun, berpeluh dan berkeluh, demi mendapatkan materi. Hanya saya sajakah? Coba renungkan, apakah saat berdoa kepada Yang Maha Memberi, hanya saya saja yang mengemis rezeki berwujud materi yang berlimpah agar hidup saya sejahtera? Saya yakin tidak.
"Fortune gives too much for many, enough to none." - Marcus Martial
Kekal tersimpan dalam pemikiran saya, “rezeki” yang setiap hari saya rapal dalam doa pada Tuhan itu merupakan rezeki materi, entah itu harta berupa uang maupun benda berwujud fisik. Parahnya, baru-baru ini alam sadar saya mulai memahami bahwa rezeki yang saya minta pada Tuhan itu sebenarnya bukan perkara benda berwujud. Terutama dalam kondisi dunia saat ini (yang saat saya menulis ini masih dilanda pandemi Covid-19) yang sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari, setiap orang berjuang keras mengejar rezeki yang mereka harap akan mampu menopang mereka untuk bertahan hidup. Menjadi pedagang, menawarkan jasa, menawarkan tenaga, dan masih banyak lagi. Saya sadar, tidak semua orang bisa melewati masa krisis ini dengan kaki berayun-ayun.
Kesadaran itu tak serta merta saya dapatkan. Saya harus dihadapkan dengan hari-hari yang selama beberapa bulan terakhir cukup menguras tenaga dan pikiran. Sejak beberapa bulan lalu, dunia memang tengah mengalami keterpurukan. Banyak rencana yang sudah disusun, banyak kegiatan yang sudah disiapkan, terpaksa harus mengalah demi keselamatan banyak nyawa. Sudah kurang lebih 7 bulan berlalu sejak pasien pertama di Indonesia dinyatakan positif Covid-19.
Menjadi sehat, bagi saya bukanlah sebuah pilihan. Menjadi sehat adalah sebuah keharusan. Nama depan saya, Saras, juga bermakna sehat, tanpa kurang suatu apapun. Sehat yang bukan hanya di fisik tubuh saja, namun juga di mental. Pikiran yang sehat, kondisi kejiwaan yang sehat, sejatinya jauh leih sulit didapat, terlebih di masa yang terbilang sulit seperti ini. Saya termasuk cukup beruntung karena tidak perlu mengunjungi psikiater atau dokter penyakit kejiwaan untuk bertahan waras. Memiliki teman-teman yang baik dan mau mendengar keluh kesah saya adalah rezeki yang selama ini tak saya anggap keberadaannya. Sistem imun jiwa yang dengan mudah akan saya aktifkan tanpa perlu bersusah payah. Dan saya tidak pernah bersyukur akan itu. Bodoh sekali.
Dua teman karib yang sudah saya kenal lebih dari 11 tahun lalu, Shindy dan Indri, mengajak saya meninggalkan pekerjaan dan kesibukan saya sejenak untuk mengunjungi Candi Prambanan, selang beberapa hari setelah Dinas Pariwisata memutuskan untuk membuka lagi tempat wisata itu agar perekonomian daerah yang selama ini terhenti karena pandemi dapat kembali berjalan. Perlahan namun pasti.
Setelah menimbang-nimbang, saya iyakan ajakan mereka. Lumayan untuk menyegarkan kembali pikiran berat yang selama ini menumpuk di kepala. Bukan. Saya bukannya tidak peduli pada kondisi pandemi dan melulu jadi penegak gerakan #diRumahAja. What I bear in mind is, “Tourism places require you to take temperature checks, examine your condition, and make sure you wash your hands with soap before entering. Businesses should be allowed to operate unless you expect them to stay closed and let people starve. Sports are gearing up to open back up as well. Until when are we going to live under the fear of "these times"?” Patuh protokol kesehatan adalah kewajiban, dan dua orang teman karib saya yang notabene bekerja sebagai tenaga kesehatan sudah mewanti-wanti saya akan ini, dan tentu saja saya sudah jauh dari sekadar mengerti.
Sebenarnya di tahun 2019, kami sudah berencana untuk berlibur ke Bangkok di pertengahan 2020, mumpung paspor saya belum habis masa berlakunya. Namun mau dikata apa, keadaan tidak mengizinkan demikian. Jadilah tamasya kecil ini sebagai obatnya.
Kami berangkat pada hari Minggu pagi, 16 Agustus 2020, sekitar pukul 07.00. Pagi yang indah, jalanan lumayan sepi dari kendaraan bermotor namun banyak pesepeda. Saat itu bersepeda memang sedang banyak peminatnya. Setelah membayar tiket (50.000 per orang), kami berjalan mengelilingi candi-candi yang entah benar-benar berjumlah seribu atau tidak. Lumayan sepi pengunjung pagi itu. Kami memotret sebanyak yang kami bisa, bercengkerama sehangat yang kami rasa, dan memahami makna rezeki yang kami punya.
Bisa bertemu teman-teman karib setelah sekian lama tak bersua di tengah pandemi yang mendera adalah rezeki yang tak terkira harganya. Lambat laun saya mulai paham bahwa segudang uang yang kita punya tak akan mampu membeli pertemanan. Bayangkan saja jika semua harus dibeli dengan uang. Berapa miliar yang saya butuhkan untuk memiliki teman-teman yang baik dan bisa memahami saya seperti mereka?
Hal inilah yang saya baru-baru ini saya pahami sebagai rezeki tak berwujud. Sejak itu, “rezeki” di pemahaman saya sudah terpendar menjadi makna yang lebih luas. Ditambah, saya mulai berpikir bahwa rezeki tak berwujud ini nilainya lebih tak terkira daripada rezeki berwujud materi. Bukankah sejatinya demikian?
Yogyakarta, 10 September 2020











g-modified.png)

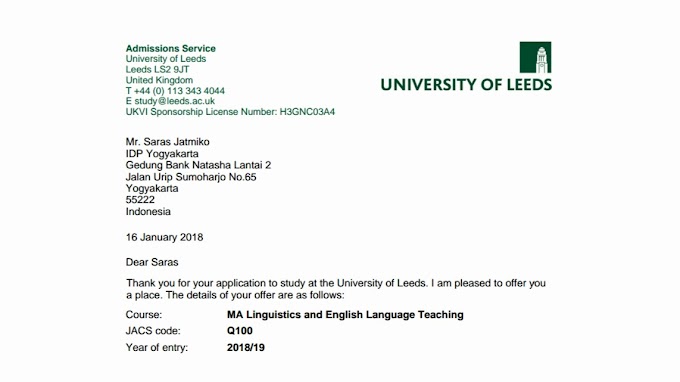




0 Comments